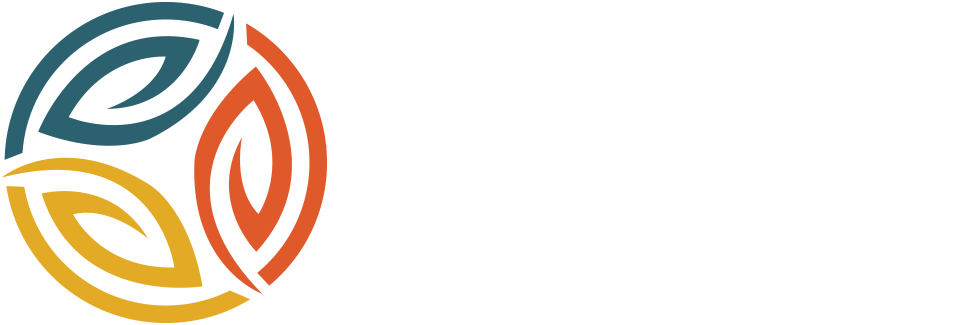Minyak jelantah ironisnya justru didaur ulang untuk digunakan kembali

Minyak jelantah ironisnya justru didaur ulang untuk digunakan kembali. Ilustrasi minyak jelantah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah mendorong program B30 yang merupakan pengembangan bahan bakar dengan sumber utama campuran minyak kelapa sawit dan solar atau biodiesel yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat impor solar, hingga berpotensi menekan emisi karbon.
Sejak 2008, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI telah menerapkan program biodiesel, yaitu dengan pencampuran solar dan FAME dari olahan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.
Per 2016, kadar FAME yang dicampurkan sebanyak 20 persen dan solar 80 persen, yang kemudian dikenal dengan B20.
Program pencampuran telah dikembangkan hingga menjadi B30 pada awal 2020. Pemerintah berencana untuk meningkatkan tingkat campuran FAME dalam biodiesel sampai dengan B50.
Namun, Engagement Unit Manager Traction Energy Asia, Ricky Amukti, mengatakan perlu ada alternatif bahan baku lainnya, seperti minyak jelantah.
Hal ini karena ada bahaya yang mengancam lingkungan jika CPO dijadikan satu-satunya bahan baku biodiesel.
“Kalau biodiesel Indonesia masih single feedstock, ini akan sangat berbahaya bagi lingkungan karena ada kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan,” kata Ricky dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (11/9).
Ricky mengatakan, tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah keberlangsungan lingkungan disokong dari lemahnya transparansi, keterlacakan, dan rekam jejak beragam persoalan yang membelenggu baik dari sisi efektivitas terhadap pengurangan emisi, pembukaan lahan, hingga ketenagakerjaan.
“Penggunaan biodiesel memang mengurangi emisi CO2. Namun, jika dihitung dari analisis daur hidup (life-cycle) dari sektor hulu (perkebunan sawit) hingga hilir (konsumsi biodiesel), alih fungsi lahan akan menyebabkan emisi CO2 yang jauh lebih tinggi,” kata Ricky.
Untuk diketahui, dari perhitungan yang pernah dilakukan Traction menunjukkan, jika emisi diesel solar fosil itu sebesar 3,14 kg CO2 equivalent per liter, maka alih fungsi dari hutan primer akan menyebabkan emisi hingga 68,61kg/CO2 equivalent per liter atau lebih dari 20 kali lipat dari emisi diesel soal fosil.
Ricky menekankan, pemerintah perlu melihat alternatif bahan baku atau feedstock lain selain sawit, agar ancaman alih fungsi lahan tidak terjadi.
Salah satu yang menjadi rekomendasinya adalah pemanfaatan minyak jelantah alias used cooking oil (UCO).
Pihaknya mengatakan, pemanfaatan UCO memiliki peluang untuk menekan emisi yang jauh lebih rendah hingga kisaran 80-90 persen dibandingkan energi yang dihasilkan dari bahan fosil.
Sebagai komparasi, jika emisi diesel solar fosil itu adalah 3,14 kg CO2 equivalent per liter, maka dengan UCO bisa hanya 0,314 persen dari emisi tersebut.
“Mengapa bisa seperti itu? Karena bahan baku UCO ini dianggap sebagai biodiesel generasi kedua atau biodiesel yang tidak langsung didapatkan dari sumber tanaman tapi dari pemanfaatan minyak yang telah digunakan untuk memasak,” kata Ricky.
Tidak sampai di situ saja, pemanfaatan UCO juga berpeluang mencegah adanya pembukaan lahan seluas 939 ribu hingga 1,48 juta hektare yang sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian dan Kesehatan masyarakat.
“Apalagi pada kenyataannya Indonesia memiliki sekitar 2,43 juta kilo liter UCO yang berhasil dikumpulkan dan diolah menjadi minyak goreng daur ulang yang sangat membahayakan untuk kesehatan. Jika UCO ini didorong untuk bahan baku biodiesel, maka masyarakat dapat menjual sisa minyak jelantahnya, dari pada menkonsumsi kembali,” kata Ricky.
Artikel ini telah tayang di republika.co.id dengan judul: “Minyak Jelantah Bisa Jadi Alternatif Biodiesel”