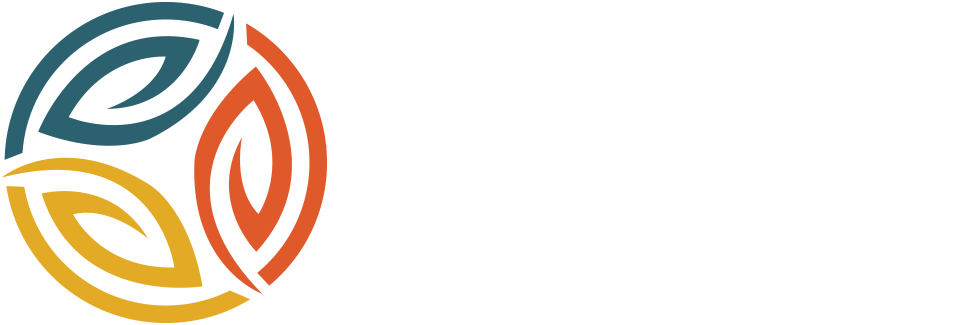© Disediakan oleh Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta – Keputusan KTT Iklim atau COP27 di Mesir pada November 2022 yang menyepakati pengucuran dana kerugian atau kerusakan untuk negara-negara miskin, disambut positif oleh Rian Ramadhan, peneliti dari Traction Energi Asia. Sebab negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk merealisasikan program terkait iklim mereka.
Menurut Rian, pertanian dan kelautan merupakan sektor yang paling terpukul oleh perubahan iklim. Paris Agreement yang berkomitmen menurunkan suhu bumi menjadi di bawah 2 derajat celcius, diharapkan bisa segera tercapai setelah suhu bumi terus naik dan mencapai puncaknya dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu Amalya Reza, Project Manager dari Trend Asia menilai pengucuran dana bantuan iklim dari negara-negara kaya harus dikaji lagi agar jangan sampai pendanaan masuk ke solusi palsu. Sebagai contoh, ada dana hibah dari Amerika Serikat ke Indonesia pada 2017 – 2018 sebesar Rp154 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik biomasa di tiga tiga desa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Namun yang terjadi, proyeknya mangkrak.
“Itu terjadi bukan karena pendanaan habis, tetapi karena implementasi tidak tepat. Ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Mentawai, ada permainan politik di situ. Pemerintah Daerah Mentawai (memberlakukan aturan) pembangkit listrik biomasa itu cuma beroperasi dari jam 18.00 – jam 24.00 (tidak 24 jam penuh). Sekarang mesinnya rusak karena sering mati – hidup. Maka, proyek itu perlu juga diawasi akuntabilitasnya,” kata Amalya, yang ditemui dalam workshop ‘Dampak Biomassa dalam Transisi Energi’, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta dengan Trend Asia, Minggu 11 Desember 2022.
Sebelumnya pada 20 November 2022, para negosiator yang hadir di COP27 berhasil menyepakati apa yang disebut dana kerugian dan kerusakan. Kesepakatan itu akan memberi kompensasi kepada negara-negara miskin yang mengalami cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan gelombang panas yang diperparah oleh emisi karbon dari negara-negara kaya.
Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemenangan yang pantas untuk keadilan iklim yang akan menguntungkan negara-negara yang telah berkontribusi sedikit terhadap polusi yang memanaskan dunia tetapi yang paling menderita. Akan tetapi kesepakatan yang lebih besar dan bisa dibilang lebih penting untuk melangkah lebih jauh dalam pengurangan emisi.
Kesepakatan yang dibuat pada 20 November 2022 tersebut, mendapat pujian dari pakar dengan menyebutnya sebagai keputusan bersejarah. Pujian di antaranya disampaikan oleh Alex Scott, pakar diplomasi iklim dari lembaga kajian E3G. Dia menyebut kesepakatan itu adalah cerminan dari apa yang bisa dilakukan ketika negara-negara termiskin tetap bersatu.
Akan tetapi, negara-negara maju masih belum menepati janji yang dibuat pada 2009 untuk membelanjakan 100 miliar euro (Rp 1,6 triliun) per tahun sebagai dana bantuan iklim lainnya. Uang itu dirancang untuk membantu negara miskin mengembangkan energi hijau dan beradaptasi dengan pemanasan global di masa depan.
Menurut Harjeet Singh, Kepala strategi bidang politik global dari Jaringan Aksi Iklim Internasional, perjanjian tersebut menawarkan harapan kepada kelompok rentan kalau mereka akan mendapatkan bantuan untuk pulih dari bencana iklim dan membangun kembali kehidupan mereka.
Artikel ini telah tayang di msn.com dengan judul: “Peneliti Lingkungan di Indonesia Tanggapi Pengucuran Dana Kerugian di COP27”