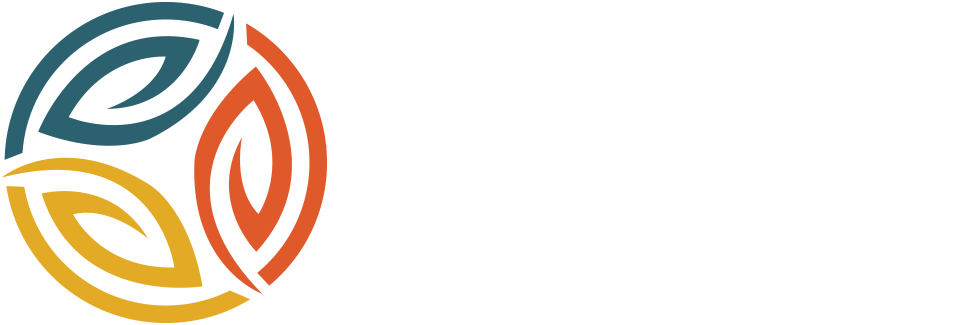Yayasan Lengis Hijau mampu memproduksi biodiesel B100 dari minyak jelantah yang dijual seharga Rp 13.000 per liter, jauh di atas harga solar subsidi.
Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) menjadi biodiesel. Menurut data Kementerian ESDM konsumsi minyak goreng rumah tangga mencapai 13 juta ton per tahun atau setara dengan 16,2 juta kilo liter (KL) pada 2019.
Dengan potensi minyak jelantah sebesar 3 juta KL per tahun, minyak goreng bekas yang dikelola dengan baik dapat mengisi 32% dari kebutuhan biodiesel nasional. Walau begitu, ada sejumlah tantangan besar dalam upaya pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel, salah satunya harga yang jauh lebih mahal dari BBM Solar.
Tri Hermawan sebagai Manager Process Engineering Yayasan Lengis Hijau mengatakan, harga jual biodiesel yang diproduksi oleh Yayasan Lengis Hijau dijual seharga Rp 13.000 per liter. Angka ini jauh lebih mahal daripada harga Solar subsidi yang dibanderol Rp 5.150 per liter.
“Dari segi harga sangat tidak bersaing. Yang beli itu hanya yang mereka peduli sama lingkungan saja,” kata Tri saat dihubungi pada Senin (25/7).
Yayasan yang bermarkas di Bali ini memperoleh suplai minyak jelantah dari hotel, rumah makan dan bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Mereka merogoh kocek Rp 4.000 per liter untuk minyak jelantah dari hotel dan rumah makan.
Sementara dari rumah tangga, mereka membelinya dengan harga Rp 6.000 per liter. Dalam sehari, Yayasan Lengis Hijau bisa mengolah 1.000 liter minyak goreng bekas menjadi bahan bakar nabati. “Yang kami produksi ini B100, karena kami tidak bisa blending. Yang punya hak itu pemerintah,“ sambung Tri.
Minyak jelantah tersebut kemudian diolah di dalam reaktor yang dibuat dari drum bekas hasil karya mandiri. Yayasan mengeluarkan biaya Rp 50 juta untuk membuat reaktor tersebut. Adapun mesin pengolahannya merupakan hasil hibah yang didatangkan dari Eropa.
Usai minyak goreng bekas itu berhasil didaur ulang menjadi biodiesel, B100 kemudian disalurkan ke sejumlah hotel, rumah makan, dan sekolah yang telah menjadi konsumen tetap.
Di sana, bahan bakar nabati (BNN) tersebut digunakan sebagai pengganti solar untuk tranportasi bus dan genset. Tri mengaku, status biodiesel yang belum populer di mata masyarakat menjadi faktor utama dari sulitnya upaya pemasaran.
Salah satu konsumen tetap biodiesel olahan Yayasan Lengis Hijau adalah Green School Bali. Sekolah internasional yang terletak di Kabupaten Badung ini memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar bus sekolah.
Tri menambahkan, B100 sebetulnya kurang cocok digunakan untuk mesin-mesin kendaraan. Bahkan, bus sekolah Green School kerap kali mengalami masalah mesin saat menggunakan BBN B100.
“Tapi sekolah itu juga dapat CSR, jadi mungkin gak begitu masalah. Kalau untuk rekomendasi ke kendaraan itu enggak ya, karena mesin kendaraan hanya mampu di B5. B100 Ini untuk mesin generator,“ ujarnya.
Harga Minyak Jelantah Tinggi
Yayasan perlu merogoh kocek Rp 13.000 per liter untuk biaya pengolahan dari minyak goreng bekas ke BBN. Beban tersebut sama dengan harga jual yang mereka tetapkan.
“Kami kan bukan murni bisnis, maka yang kami hitung itu hanya dari biaya jual saja. Tidak termasuk biaya investasi mesin. Kalau untuk segi bisnis, biodiesel agak sulit,“ tutur tri.
Dia pun mengatakan yayasan kerap kali kesulitan mendapatkan bahan baku minyak jelantah. Pasalnya, para produsen minyak jelantah seperti hotel dan rumah makan enggan memberikan jelantah mereka dengan harga Rp 4.000 per liter.
Mereka lebih memilih menjual ke pengepul besar yang mampu membeli sesuai dengan harga pasaran yang lebih tinggi, yakni Rp 5.500-6.000 per liter. “Kenapa harga minyak jelantah tinggi? karena kebutuhan untuk Eropa itu tinggi, untuk ekspor. Ini bukan limbah lagi, tapi ini komoditas,“ ucapnya.
Tri berharap, pemerintah bias membuat regulasi yang mengatur soal pengumpulan jelantah dari rumah tangga, hotel, maupun rumah makan agar bisa diberdayakan menjadi bahan baku biodiesel.
Adapun regulasi soal pengumpulan minyak jelantah sudah diterapkan di Kota Bogor. Di wilayah tersebut, cerita Tri, Pemerintah Kota Bogor secara berkala mengambil minyak goreng bekas dari hotel dan rumah makan secara gratis. Minyak jelantah tersebut kemudian diolah menjadi campuran biodiesel untuk bahan bakar Trans Pakuan.
“Regulasi di tingkat daerah itu lebih efektif, karena pemerintah daerah yang lebih mengerti dari sisi karakter dan kondisi masyakaratnya. Kalau dari pemerintah pusat mungkin agak sulit karena harus membuat turunan peraturan dan sebagainya,“ harap Tri.
Direktorat Bionergi Kementerian ESDM, Edi Wibowo, mengatakan biodiesel yang dihasilkan dari UCO memiliki peluang untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun ekspor. Menurutnya, pemanfaatan biodiesel dari UCO dapat menghemat biaya produksi hingga 35% dibandingkan dengan biodiesel berbasis CPO.
Adapun pemanfaatan UCO tidak terbatas untuk biodiesel semata, ia bisa digunakan sebagai bahan campuran bioethanol, bioavtur, dan Biofuel yang terhidrogenasi (HVO). “Selain itu, juga mengurangi 91,7% emisi CO2 dibandingkan dengan solar,” kata Edi dalam Katadata IDE 2022, Kamis (7/4).
Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang muncul dalam upaya pengembangan UCO untuk bahan bakar nabati, di antaranya fluktuasi harga minyak jelantah yang relatif tinggi hingga Rp 6.000 per liter, mekanisme pengumpulan dari rantai pasok yang belum terbentuk, terutama yang melibatkan komunitas masyarakat dan pemetaan potensi.
“Harus masifkan sosialisasi terkait bahaya penggunaan minyak jelantah untuk memasak dan promosi pemanfaatan minyak jelantah untuk energi,” ujar Edi.
Manager Riset Traction Energy Asia, Fariz Panghedar, menjelaskan total potensi UCO dari rumah tangga dan unit usaha mikro di kota-kota besar seperti Pulau Jawa dan Bali mencapai 207.170,65 KL per tahun. Sementara total potensi UCO dari rumah tangga dan unit usaha mikro di level nasional sebesar 1.243.307,7 KL per tahun.
“Total potensi ini hanya di rumah tangga dan unit usaha mikro, apabila diluaskan ke unit skala kecil, sedang dan menengah di sektor makanan, termasuk juga sektor hotel dan restoran serta kafe maka jumlahnya akan 3 juta KL per tahun. Itu yang bisa dimanfaatkan sebagai BBN,” jelasnya.
Ia melanjutkan, saat ini sebagian besar permintaan bahan bakar nabati biodiesel berasal dari sektor maritim. Oleh karenanya, Fariz mengusulkan agar memfungsikan sejumlah tempat seperti pelabuhan dan perumahan warga di kota-kota besar dan padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera sebagai sentra pengumpulan minyak jelantah.
“Kemudian itu bisa disitrubusikan lebih dulu ke kilang-kilang dan didistribusikan di lokasi yang sama dengan lokasi pengepulan. Ini bisa digunakan sebagai bahan bakar di mesin-mesin yang kecepatannya rendah seperti genser, forlift, dan boiler,” ujar Fariz.
Adapun distribusi dari hasil tersebut dapat disalurkan ke Kawasan industri di Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki potensi industri yang besar. Selain itu, karena permintaan biodiesel mayoritas berada di sektor maritim, bahan bakar nabati tersebut dapat disalurkan ke beberapa wilayah persisir.
“Untuk kegiatan pelayaran dan perikanan di daerah Kendal, Semarang, Surabaya bisa menyediakan sektor perikanan dan industri,” tukas Fariz.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Harga yang Tinggi Jadi Momok Serapan Biodiesel Minyak Jelantah”